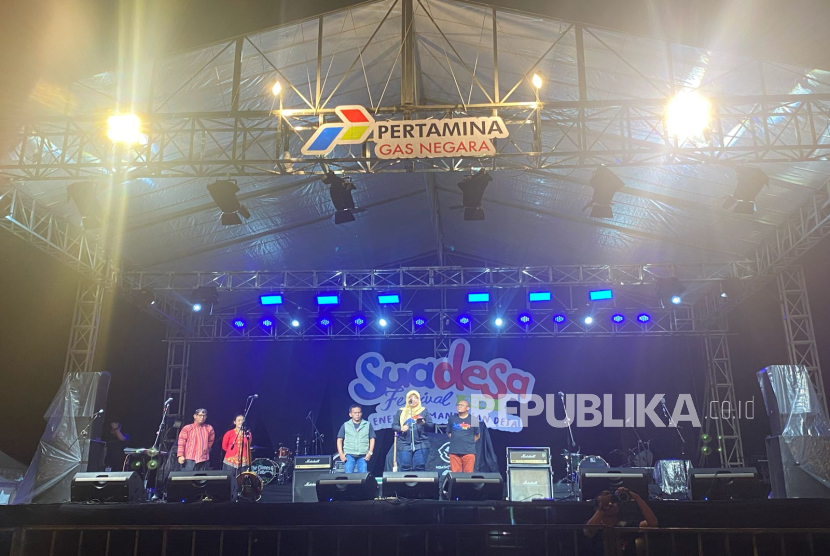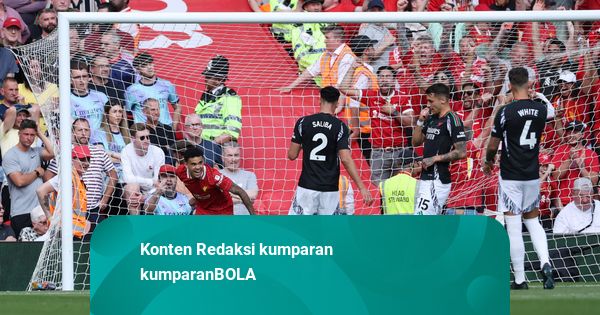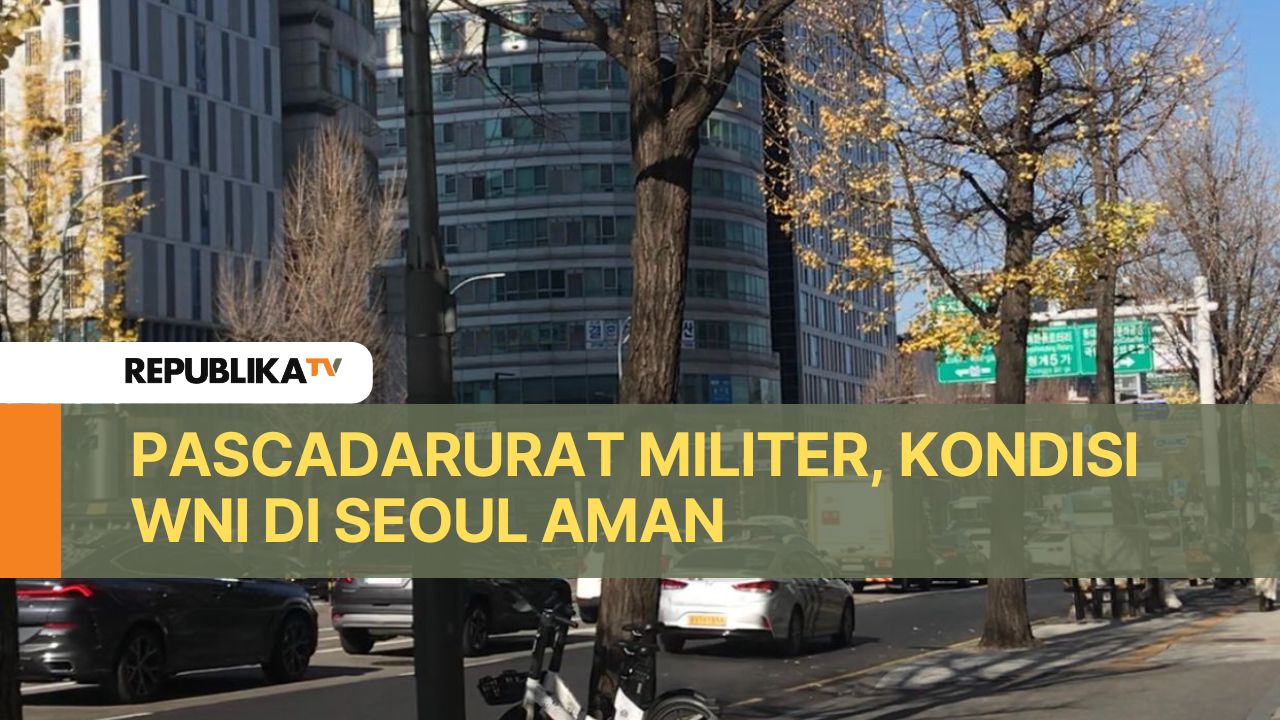(MI/Seno)
(MI/Seno)
PADA 19 Desember 2024 lalu Metro TV menggelar diskusi dengan menteri dan para rektor tentang pendidikan. Minimal ada dua isu penting yang dibahas dalam diskusi tersebut, yaitu akses dan kualitas pendidikan. Dua isu itu penting mengingat saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan dan peluang untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kata kunci untuk menghadapi tantangan tersebut ialah, bagaimana kesiapan kualitas sumber daya manusia (SDM). Apalagi saat ini kita tengah dianugerahi bonus demografi, terlihat dari angka ketergantungan yang mencapai titik terendah 46,9% pada 2030. Artinya, jumlah penduduk usia tidak produktif lebih rendah daripada jumlah penduduk usia produktif. Kita patut bersyukur mengingat kini banyak negara lain yang telah memasuki aging society, yaitu penduduk usia lansia semakin meningkat dan bahkan lebih tinggi daripada penduduk usia produktif, seperti Jepang.
Momentum bonus demografi ini harus kita respons dengan peningkatan kualitas SDM, yang salah satu langkahnya ialah dengan meningkatkan akses pendidikan tinggi. Salah satu ukuran akses pendidikan ialah angka partisipasi kasar (APK). APK pendidikan tinggi menunjukkan perbandingan jumlah mahasiswa dengan jumlah penduduk usia 19-23 tahun. Data menunjukkan bahwa APK pendidikan tinggi Indonesia 31,45, yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Filipina (35,52%), Malaysia (43%), Thailand (49,29%), Jepang (70%), Singapura (91,09%), dan Korea Selatan (92%). Mengapa APK kita lebih rendah daripada negara-negara lain? Faktor-faktor apa saja penyebab rendahnya APK pendidikan tinggi kita?
Peta lulusan SLTA
Menurut data pemerintah saat ini terdapat 4.356 perguruan tinggi dengan komposisi 92% swasta dan hanya 8% negeri. Jumlah mahasiswa mencapai 9,8 juta orang, jumlah dosen 338,2 orang, dan jumlah program studi 32.592.
Tentu jumlah mahasiswa tersebut akan semakin meningkat bila semakin banyak lulusan SLTA yang melanjutkan studi. Namun faktanya, para lulusan SLTA sebagian besar tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Ada sekitar 3,7 juta pelajar yang baru lulus jenjang SLTA setiap tahunnya, dan hanya 1,8 juta pelajar lulusan SLTA yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian, ada 1,9 juta pelajar yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi.
Kalau kita petakan para lulusan SLTA tersebut, setidaknya ada empat tipe. Tipe pertama ialah lulusan SLTA yang memiliki kualitas akademis tinggi dan berasal dari keluarga mampu. Tipe ini tentu tidak bermasalah dan potensial menuntaskan pendidikan di perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
Tipe kedua ialah lulusan SLTA yang memiliki kualitas akademis tinggi tapi berasal dari keluarga tidak mampu. Di sinilah program beasiswa menjadi penting untuk membantu kalangan ini. Perhatian banyak pihak ditujukan kepada kalangan ini sehingga beragam beasiswa baik bersumber dari dana pemerintah, organisasi sosial, maupun swasta terus berkembang.
Saat ini berkembang pula program wakaf deposito yang mengundang donator untuk menempatkan dananya dalam periode tertentu, dan hasil penempatan dana tersebut dipergunakan untuk beasiswa. Himpunan Alumni IPB telah menggalang dana melalui mekanisme ini. Begitu pula ICMI, telah memulai usaha yang sama.
Tipe ketiga ialah lulusan SLTA yang memiliki kualitas akademis rendah tapi berasal dari keluarga mampu. Tentu tipe ini relatif tidak bermasalah mengingat mereka masih memiliki modal finansial untuk menentukan langkah selanjutnya, baik berwirausaha maupun melanjutkan studi.
Tipe keempat ialah lulusan SLTA yang memiliki kualitas akademis relatif rendah dan juga berasal dari keluarga tidak mampu. Diduga sebagian besar dari 1,9 juta pelajar yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi berasal dari tipe ini. Tipe inilah yang kini mestinya mendapat perhatian khusus mengingat mereka akan dihadapkan pada masalah kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
Mereka memiliki keterbatasan keterampilan yang diperlukan dunia kerja. Bila tidak tertangani dengan baik, ancaman pengangguran akan semakin meningkat dan pada akhirnya berpotensi menjadi beban pembangunan. Terhadap kelompok ini diperlukan intervensi khusus.
Faktor-faktor
Rendahnya APK pendidikan tinggi di Indonesia diduga disebabkan sejumlah faktor. Pertama, keterbatasan akses baik secara geografis maupun infrastruktur. Banyak daerah terpencil di Indonesia sulit dijangkau yang juga menyulitkan siswa di daerah tersebut untuk melanjutkan studi karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi. Begitu pula fasilitas pendidikan yang kurang merata membuat siswa kesulitan untuk kuliah.
Kedua, isu kualitas pendidikan menengah. Tidak semua pendidikan SLTA memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas SLTA yang rendah bisa berdampak pada rendahnya kualitas lulusannya. Termasuk di dalamnya ialah rendahnya minat siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi.
Ketiga, tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Di satu sisi perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang relatif tinggi dan di sisi lain jumlah beasiswa juga terbatas. Tentu situasi ini berbeda dengan kondisi di Jerman yang membebaskan biaya kuliah untuk mahasiswa.
Keempat, faktor sosiologis. Masih banyak persepsi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahwa meneruskan studi ke pendidikan tinggi tidak penting. Apalagi bagi kaum perempuan yang di sebagian kelompok masyarakat dipersepsikan sebagai orang yang hanya berperan dalam urusan domestik rumah tangga, sehingga dianggap tidap terlalu penting untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selain itu, rendahnya cita-cita siswa untuk masa depan berpengaruh terhadap motivasi untuk melanjutkan studi setinggi-tingginya.
Rendahnya APK pendidikan tinggi ini tentu bisa berdampak kepada kualitas SDM kita mendatang. Kondisi bonus demografi yang kita alami saat ini tentu tidak akan berarti apa-apa kalau kualitas SDM kita terbatas. Dominasi SDM usia produktif dengan kualitas rendah akan bisa berdampak pada peningkatan pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap daya saing bangsa.
Strategi
Upaya peningkatan APK pendidikan tinggi perlu dilakukan secara komprehensif. Setidaknya ada lima strategi yang diperlukan. Pertama, pengembangan universitas digital yang memiliki fleksibilitas dalam waktu dan tempat. Hanya universitas digital yang mampu menjangkau jumlah mahasiswa dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital sehingga dapat diakses pelosok Nusantara.
Kedua, pengembangan akademi komunitas diploma 1 dan 2. Strategi ini penting bagi lulusan SLTA tipe 4 di atas, di mana mereka memerlukan pendidikan vokasi satu hingga dua tahun sehingga bisa langsung kerja. Dalam hal ini perusahaan swasta dapat menjadi motor pemggerak akademi komunitas yang program pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja di perusahaannya. Sebagai contoh, perusahaan sawit bisa menyelenggarakan program ini dengan menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswanya. Setelah lulus, mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Di sinilah kemitraan swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah diperlukan. Perusahaan-perusahaan besar perlu mengembangkan program ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.
Ketiga, peningkatan jumlah beasiswa, yang berasal tidak saja dari pemerintah, tetapi juga dari swasta dan masyarakat luas. Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI) menggelar konser amal yang ternyata dalam 2 jam bisa mendapatkan hampir Rp3 miliar untuk beasiswa. PGA IPB setiap tahun menggelar charity tournament untuk mengumpulkan dana beasiswa. Kini crowd funding juga menjadi bentuk baru penggalangan dana untuk beasiswa.
Keempat, peningkatan kualitas pendidikan menengah. Masa depan perguruan tinggi ditentukan oleh kualitas pendidikan menengah, baik kurikulum, fasilitas, maupun tenaga guru. Hal ini karena input bagi perguruan tinggi berasal output SLTA. Oleh karena itu, minimal pendidikan menengah membekali siswanya dengan pola pikir baru tentang pentingnya memasuki dunia pendidikan tinggi.
Kelima, penetapan wajib belajar 12 tahun. Untuk memastikan bahwa semakin banyak lulusan SLTA masuk ke perguruan tinggi, kita juga perlu memastikan semakin banyaknya lulusan SLTP yang masuk SLTA. Oleh sebab itu, penetapan wajib belajar 12 tahun harus segera diwujudkan untuk menggantikan wajib belajar 9 tahun.
Ini merupakan upaya tidak langsung peningkatan APK pendidikan tinggi, tapi sangat diperlukan. Sekaligus ini menggambarkan bahwa APK pendidikan tinggi berhubungan dengan proses pendidikan sebelumnya sehingga kebijakan pendidikan nasional ...

 4 months ago
4
4 months ago
4